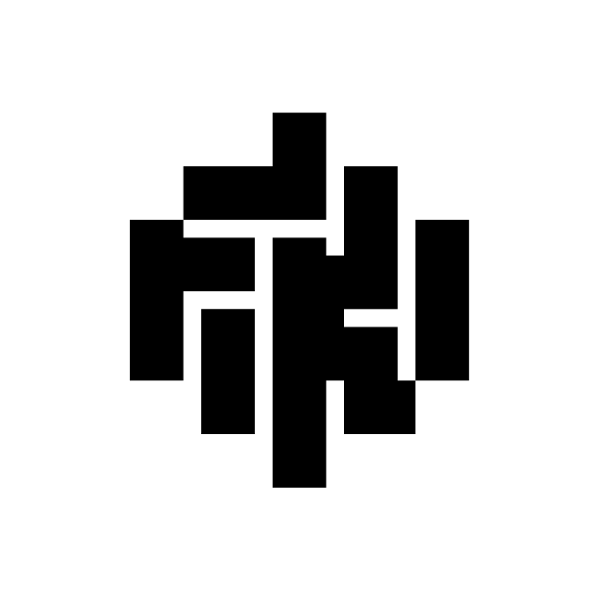Kring!
Telepon genggamku berbunyi, tepat setelah Silvi
selesai mencium punggung tangan kananku untuk berpamitan. Dia bersama
teman-teman lainnya seketika berhamburan. Berjalan riang cekikian. Mereka
bergegas pulang menuju rumah masing-masing.
Pesanan sudah sampai rumah, Mbak. Terimakasih.
Aku memandangi layar teleponku. Tersenyum. Satu pesan singkat baru saja mendarat. Kubaca. Paket berisi sepuluh potong kerudung akhirnya sampai di tangan pembeli asal Kota Padang. Alhamdulillah.
sebenarnya aku cukup kuatir. Aku kira akan ada kendala dalam pengiriman
antarpulau kali ini karena kabut asap yang sedang melanda beberapa kota di
Sumatera maupun Kalimantan.
“Mas, masih di pasar? Udah selesai belanja
kainnya? Ini aku udah mau ke rumah. Cepat pulang, ya! Hati-hati di jalan! Aku
tunggu.”
Segera kukirim pesan pendek kepada Mas Danang yang
mungkin masih bergumul dengan ramai para pembeli. Sebenarnya tadi aku ingin
ikut, menemaninya berburu bahan dasar pembuatan produk kerudung dan gamis bisnis
kami. Namun dia tak mengizinkan. “Ndak usah. Kamu di rumah aja, ya. Toh nanti
sore kan kamu ada tugas ngajar anak-anak,” katanya.
Menjadi sales promotion girl di sebuah brand rokok
saat masa kuliah, kemudian berpindah menjabat teller di salah satu bank swasta
setelah wisuda sampai sebulan pascanikah. Dua pengalaman itu sekelebat terkenang.
Terkadang merasa heran, bisa-bisanya aku dulu merasa nyaman menggelutinya. Tapi
biarlah, masa lalu itu sudah nyata berlalu.
Semoga Allah memberi ganti pekerjaan yang lebih
baik, yang produk dan sistemnya halal, serta tak mengandung unsur keburukan, bahaya,
ataupun riba.
Aku teringat nasihat itu.
Aku teringat nasihat itu.
Dan perkara ingin membantu suami mencari nafkah,
maka syaratnya tidak melupakan tanggung jawab keluarga. Sebab oleh Nabi
Muhammad, dikatakan bahwa raiyatun fi baiti zaujiha: bahwa istri sebagai pemimpin,
pengatur, serta penjaga rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya itu. tutup tutur ustadz pembimbingku, kala aku
berkonsultasi kepadanya terkait profesiku saat itu.
Kini, aku mantap dengan aktifitasku: menjadi guru
ngaji dan partner wirausaha Mas Danang. Senang sekali bisa melakukan hal-hal
yang bermanfaat serta tanpa terkekang oleh ikatan waktu sebagaimana kerja
kantoran. Hari-hariku pun jauh lebih banyak di rumah. Nikmat ini benar-benar
aku syukuri.
Kumasukkan handphone ke dalam tas kecilku.
Kuletakkan dan kurapikan kembali beberapa kitab suci di sudut rak dekat
jendela. Bangku-bangku kutepikan ke samping kanan-kiri ruangan. “Alhamdulillah,
sore yang penuh berkah,” ucapku seraya keluar ruangan menuju teras depan.
Sepeda pancal yang terparkir sendirian di sebelah timur tempat wudu itu
sepertinya sudah tak sabar untuk dikayuh.
∙∙∙
Namaku Diana, seorang wanita yang sudah dikaruniai
suami yang baik, dan berusaha pula menjadi istri yang baik.
Usia pernikahan kami baru setengah tahun.
Masih baru memang. Namun rasanya sudah banyak warna kehidupan yang telah kami ronai.
Aku mualaf. Resmi memeluk Islam sebulan sebelum pernikahanku
dengan Mas Danang. Orangtua serta keluargaku sempat menolak keras atas keinginanku
beralih keyakinan, lebih-lebih mereka tergolong nonmuslim yang taat beragama. Namun
Islam terlanjur mengambil hatiku sejak dulu, sejak aku duduk di bangku sekolah
bersegaram putih abu-abu.
Aku tetap teguh, serta sedikit demi sedikit kucoba
lelehkan hati keluargaku. Syukurlah berhasil. Perlahan orangtuaku luluh. Agama yang
sempurna ini pun sempurna kurengkuh. Dan serasa tak percaya, berkah berlapis datang
kepadaku tak lama setelah keislamanku. Aku dipinang oleh seorang pemuda, murid
ustad pembimbingku.
“Apa yang membuatmu tertarik masuk Islam?” Mas
Danang pernah bertanya kepadaku.
Sejatinya ada banyak hal dari Islam yang
menjadikanku terkesan. Dan selain Al Quran, ada satu lagi yang paling menarik hati waktu
itu.
Adalah hijab, kain lebar–terdiri dari kerudung dan
gamis–ini setia menutupi hampir seluruh anggota tubuh para wanita muslimah,
termasuk teman-temanku. Entah saat di sekolah maupun saat kegiatan lainnya di
luar rumah. Kala mereka memakainya, aku justru melihat pancaran kecantikan dan
keanggunan.
“Karena ini perintah,” jawab salah satu temanku
dulu, saat aku bertanya kenapa ia dan teman-teman muslimah lainnya mengenakan hijab.
Ya, sekalipun berhijab terkadang baru disadari
bahwa ia menjaganya dari pandangan serta gangguan lelaki. Sekalipun ia juga ternyata
bisa melindunginya dari terik matahari ataupun dinginnya malam, dan deretan
fungsi yang lain. Namun jawaban itulah yang memang patut diucap di awal: 'karena
ini perintah’.
Karena perintah, maka manusia sebagai yang dicipta
harus tunduk dan patuh terhadap yang mencipta. Karena perintah, maka itulah
yang utama meskipun tabir padat manfaat atas apa yang diperintahkan itu yang lebih kentara. Maka itu pula yang
mula-mula biarpun mungkin belum juga kita dapati kegunaannya. Karena ini perintah
dari Sang Maha Pencipta, maka tak perlu ragu. Lakukan saja.
Sehingga jika sebaliknya, payah terasa sebuah
perintah, maka tetap patut taat. Maka bila tiba berhijab terasa berat, terasa
ribet saat mengenakan, terasa rambut terkusutkan, terasa panas dan menggerahkan,
terasa pekerjaan terbebankan, maka kita tetap mengenakannya sembari tegas mengucap 'karena ini perintah'.
“.. Kemudian, apa yang meyakinkanmu menerima
pinanganku? Terlebih bukankah aku sama sekali masih sebagai lelaki asing bagimu.”
Mendengarnya, saat itu aku sejenak tersenyum dan
memandanginya, kemudian menggenggam erat tangannya. “Karena ketaatanmu pada
Islam, Mas, dan baik budi pekertimu,” jawabku kepada Mas Danang.
“Hmm,, beneran? Emang tau dari mana?” Tanyanya semacam
menggodaku.
“Ada deh!” Kulepas genggamanku dan kusahut dengan agak sebal. Namun seketika dia
meraih tanganku, menjawatnya erat dan tertawa ringan.
∙∙∙
Tak sampai waktu magrib, aku sudah tiba di rumah.
Mengendarai sepeda pancal hanya butuh waktu lima menit dari masjid kecil itu–tempat
baru saja aku mengajar Al Quran–menuju kompleks tempat tinggalku.
Mas Danang belum terlihat batang hidungnya. Dia belum
pulang dari aktifitas belanjanya di pasar. Rumah yang baru genap tiga pekan kami beli dan
tempati ini pun masih sepi. Karena sekalipun dia sudah datang, maka hanya kami
berdua penghuninya.
Maklum, pasangan muda ini memang sudah merindu
hadirnya sang buah hati. Bila saja ayah-ibuku saat ini ada di sebelahku,
mungkin–setelah kesekian kalinya–akan kembali berkata, “Makanya biar ndak sepi,
sini balik sama bapak-ibu lagi.”
Dari enam bersaudara yang semuanya sudah menikah
dan menetap di luar kota, aku satu-satunya anak perempuan. Anak terakhir pula.
Maka tak heran orangtuaku sangat mengharapkanku–bersama suami–tinggal dengan mereka.
Sekalipun tak sampai menjadi syarat, namun hal itu mereka ungkapkan sejak awal,
sebelum aku menikah.
Namun setali tiga uang, demekian juga dari pihak Mas
Danang. Orangtuanya ingin Mas Danang nantinya tinggal bersama keluarganya.
Maka bak terjadi tarik tambang antarkubu keluarga, mereka saling seret satu sama lain. Sehingga saat pertemuan antarfamili itu, selepas
bincang-bincang penentuan hari akad dan resepsi, Mas Danang mengajukan sesuatu
yang tak mengiyakan keduanya. Yakni bermukim sendiri.
Alhamdulillah. Sekian menit berdiskusi, akhirnya disetujui.
“Terus, nantinya mau tinggal di mana? Apa sudah punya rumah?” tanya ayahku. “Entah,
Pak. Rumah juga belum ada. Tapi urusan itu insyaallah mudah,” jawab Mas Danang pascalamaran.
“Sejatinya sejak awal dulu, aku pribadi memang berhasrat
tinggal beratap sendiri,” cerita suamiku kepadaku suatu malam, tiga hari
sesudah akad terucap.
“Benar adanya bahwa bersama orangtua, hadir
pendampingan dan bimbingan bagi pasangan yang masih awal menikah. Bersama
orangtua, datang bantuan dan manfaat bagi anaknya yang baru menjalani kehidupan
rumah tangga. Saking sayangnya orangtua, seakan ingin selalu hadir di setiap urusan buah hatinya.”
“Namun bagaimanapun juga,” sambungnya kala dingin
mulai merambat ke ruang tamu rumah kontrakan ala kadar yang kami huni, “layaknya
sekapal dua nakhoda, kurang pas rasanya jika serumah berkeluarga ganda, dua kepemimpinan.
Sangat rentan tumbuh pundi-pundi beda pendapat. Cukup mungkin muncul
‘perselisihan’ yang akan kuat menjalar dan merunyam. Dan biarpun bisa jadi tak
sampai mencuat konflik terbuka, namun konflik batin sulit terelak, setidaknya
bersemayam, yang siap-siap saja sewaktu-waktu meledak.”
“Betapapun juga, sekapal dua nakhoda cukup
sensitif serta berkonsekuensi. Alangkah baiknya sebisa mungkin dihindari.”
∙∙∙
Bergegas aku menuju kamar mandi. Waktunya membersihkan
diri kemudian salat magrib.
Bada salat, aku melanjutkan menyiapkan hidangan. Rumah
masih saja hening. Tak juga terdengar suara apapun tanda kehadiran seseorang. Layar
telepon genggam yang dari tadi kutaruh sebelah talenan juga tetap saja redup, tak
menampakkan sinar terang tanda ada kabar panggilan atau pesan pendek sekalipun.
Ah, ini ya yang namanya cinta. Selalu menanti yang
sejenak pergi. Jatuhnya kian rindu kala tak jua bersambut temu. Rasanya tak
sabar segera menyambar, menyambut dia pulang. Kesannya sudah sekian pekan
berpisah, padahal baru tadi pagi, yang itu cuma sekian jam saja.
Tok.. Tok.. Tok! Ketukan pintu depan rumah
terdengar olehku yang masih sibuk di dapur.
“Assalamualaikum.” Suara yang tak asing terdengar.
“Waalaikumsalam.” Aku tersenyum seraya bergegas
menghampirinya. Aku tahu itu dia. Mas Danang datang!
mlg/20/10/15